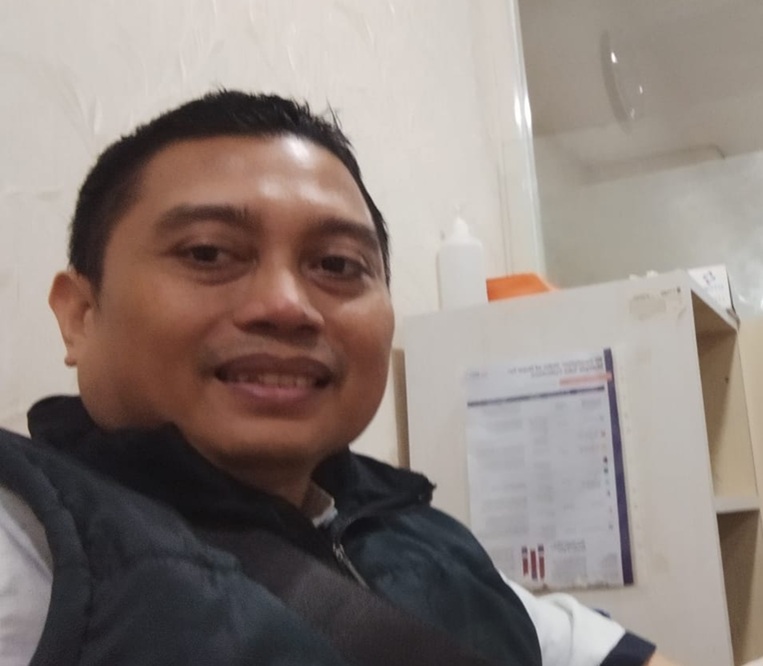
Oleh: Dr. Rudy (Penulis adalah Dosen Praktisi pada Universitas Megaresky Makassar dan Universitas Sulawesi Tenggara)
Indonesia sebagai negara hukum tentunya sangat menjunjung tinggi supremasi hukum yang berlaku dan diposisikan sebagai alat untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga penegakan hukum menempati posisi yang sangat sentral, dimana negara menempatkan hukum dalam fungsinya sebagai alat pengatur bagi kehidupan bermasyarakat baik hubungannya dengan penguasa maupun antara masyarakat itu sendiri. Hukum dan masyarakat seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Berlakunya hukum didalam suatu tatanan sosial yang disebut masyarakat, oleh bangsa Romawi disebut sebagai ubi societas ibi ius yang menggambarkan betapa eratnya hubungan antara hukum dan masyarakat. Salah satu masalah terbesar dalam sistem peradilan pidana Indonesia adalah fenomena bolak-baliknya berkas perkara antara penyidik dan jaksa. Proses ini sering kali menghambat efisiensi peradilan dan memperpanjang waktu penyelesaian perkara. Di beberapa negara, jaksa tidak hanya sekadar menerima berkas perkara dari penyidik, tetapi juga berhak memberikan arahan penyidikan kepada penyidik. Hal ini memungkinkan perkara dapat ditangani lebih cepat tanpa perlu berkali-kali mengembalikan berkas karena tidak lengkap. KUHP nasional (UU No 1 Tahun 2023) semakin memperkuat peran jaksa dalam pengawasan proses peradilan. Pasal 132 KUHP nasional secara eksplisit menyebutkan bahwa penuntutan merupakan bagian dari proses peradilan yang dimulai sejak tahap penyidikan, menandakan bahwa jaksa memiliki peran aktif dalam memastikan kelengkapan suatu perkara sebelum diajukan ke pengadilan.
Koordinasi antar lembaga Negara, khususnya penegak hukum masih menjadi pekerjaan rumah terbesar pemerintahan sekarang dalam hal reformasi hukum. Perlunya reformulasi dan rekonstruksi peraturan yang diharapkan jaksa dapat hadir pada saat dilakukan penyidikan. Intervensi dapat dilakukan dengan metode prapenuntutan, sehingga setiap tindak pidana atau perbuatan dapat menjadi semakin jelas dan besar kemungkinan terhindari dari hal-hal yang nantinya dikhawatirkan akan mempengaruhi pembuktian dalam penuntutan. Hal yang paling utama adalah perlu kesatuan rasa antara penyidik dan penuntut umum sebagai sub sistem dari satu kesatuan Sistem Peradilan Pidana. Keduanya “wajib” bersama-sama membangun citra tanpa merendahkan satu sama lain, karena baik buruknya hasil kerja adalah mutlak kinerja bersama. Dalam melaksanakan kerjasama penanganan perkara pidana, penyidik maupun penuntut umum harus selalu mengingat tujuan yang ingin dicapai selain kepastian hukum dan kemanfaatan yaitu keadilan. Ketiga nilai dasar ini juga disebut sebagai cita hukum (idee des recht).
Dalam teori hukum Rechtsstaat, setiap proses hukum harus mengedepankan prinsip keadilan (justitia), kepastian hukum (certitudo juris), dan kemanfaatan hukum (utilitas juris). Jika kejaksaan tidak memiliki kewenangan untuk mengawasi penyidikan secara langsung, maka terdapat risiko terjadinya penyimpangan dalam proses pencarian bukti dan penerapan hukum. Prinsip fruit of the poisonous tree, yang berkembang dalam sistem common law, menunjukkan bahwa jika suatu bukti diperoleh secara tidak sah (illegal evidence), maka seluruh hasil penyidikan yang bersumber dari bukti tersebut menjadi tidak sah. Oleh karena itu, kejaksaan sebagai pengendali perkara harus memiliki otoritas dalam memastikan bahwa alat bukti dikumpulkan secara sah (legitima probatio).
Polemik tentang amandemen Rancangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (R-KUHAP) semakin mengemuka, sejalan dengan dimulainya pembahasan di DPR RI pada masa sidang 2024-2025. RUU ini diagendakan akan berlaku bersamaan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah disahkan, dan akan diberlakukan pada 1 Januari 2026. Namun, dalam proses reformasi hukum yang sangat diharapkan, masih ada sejumlah celah dan potensi masalah yang muncul, khususnya terkait penguatan asas dominus litis. Distribusi kewenangan yang dianggap terlalu besar kepada lembaga Adhyaksa dalam R-KUHAP ini, menimbulkan kekhawatiran terkait tumpang tindih kewenangan hingga rentan penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini juga dapat menghilangkan mekanisme check and balance dalam sistem peradilan pidana antara lembaga penegak hukum, yang pada gilirannya menjadikan kejaksaan sebagai institusi “superbody”, sulit dikendalikan, dan rentan terhadap penyimpangan.
KUHAP yang berlaku saat ini tidak menerapkan prinsip dominus litis atau kewenangan mutlak yang diberikan kepada kejaksaan dalam proses penanganan perkara pidana. Hal tersebut mengakibatkan posisi jaksa selaku penuntut umum dipandang kurang, karena hanya memeriksa secara formal berkas perkara saja, tidak mengetahui proses dari mulai penyidikan termasuk dalam penyusunan berkas perkara dan tata cara perolehan alat bukti. KUHAP yang secara implisit memuat prinsip spesialisasi maupun diferensiasi tidak hanya membedakan dan membagi tugas, serta kewenangan antar instansi, melainkan juga menetapkan tapal batas yang jelas dalam hal pertanggungjawaban untuk setiap lingkup kewenangannya. Mulai dari proses penerimaan laporan atau pengaduan, hingga eksekusi terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pola ini dikenal sebagai Integrated Criminal Justice System, yang merujuk pada suatu proses pidana yang terpadu antara sub-sistem penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan hingga berakhir pada sub-sistem pelaksanaan putusan pengadilan. Tujuan dari sistem ini untuk mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan (kewenangan) yang berlebihan pada satu lembaga tertentu. Meskipun KUHAP menjadi induk utama pedoman hukum pidana formil di Indonesia, namun realitanya setiap lembaga penegak hukum mempunyai kewenangan masing-masing mengatur secara khusus dalam undang-undang di luar KUHAP. Misalnya, kewenangan Kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Kejaksaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, serta kewenangan Pengadilan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.
Dominus litis adalah asas yang memberi kewenangan kepada kejaksaan untuk mengendalikan proses penuntutan pidana. Istilah ini berasal dari bahasa Latin yang berarti “penguasa perkara”, yang artinya dalam proses peradilan pidana, jaksalah yang berwenang apakah suatu perkara dapat dilakukan penuntutan ke pengadilan atau tidak. Secara filosofis, konsep ini berakar pada prinsip ius puniendi yakni hak negara untuk menghukum individu yang melanggar hukum. Dalam konteks ini, kejaksaan memiliki tanggung jawab sebagai perwujudan kekuasaan negara dalam penegakan hukum dengan mengontrol jalannya perkara guna mencapai keadilan substantif (justitia substantialis). Dalam sistem hukum kontinental atau civil law yang dianut oleh banyak negara, termasuk Indonesia, peran dominus litis biasanya dipegang oleh jaksa penuntut umum karena ia memiliki kewenangan melakukan penuntutan dan mengajukan perkara ke pengadilan. Selain itu, kejaksaan diberikan kewenangan luas melakukan pengawasan terhadap proses penyidikan berdasarkan asas opportunite de poursuites atau principle of opportunity yaitu kebebasan untuk menentukan apakah suatu kasus layak untuk diajukan ke pengadilan atau tidak. Sejarah konsep ini dapat ditelusuri dalam sistem hukum Romawi yang menganut prinsip accusatio directa, di mana jaksa selaku penuntut umum memiliki peran utama dalam mengajukan dan mengendalikan proses hukum terhadap seorang terdakwa. Di Indonesia, konsep ini mengalami perubahan dari sistem inquisitoire, yang memberikan peran dominan kepada kejaksaan dalam Herziene Indonesisch Reglement (HIR), menjadi sistem accusatoir yang lebih membatasi kewenangan kejaksaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang saat ini berlaku. Posisi dan fungsi kejaksaan sebagai dominus litis sebenarnya sangat jelas dalam ketentuan (HIR). Pada masa berlakunya HIR, penyidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses penuntutan (unité de poursuite et d’instruction). Hal ini menjadikan jaksa penuntut umum sebagai koordinator penyidikan (coordinator investigationis) sekaligus memiliki kewenangan melakukan penyidikan sendiri (opsporing). Untuk itu, kejaksaan menempati posisi sebagai instansi kunci (key figure) dalam keseluruhan proses penyelenggaraan hukum pidana dari tahap awal hingga akhir (ab initio ad finem).
Konsep dominus litis memberikan peran sentral kepada kejaksaan sebagai pengendali utama proses hukum dalam perkara pidana, mengadopsi model sistem hukum kontinental atau civil law tersebut di atas. Dalam implementasinya, Kejaksaan akan memiliki wewenang lebih luas, mulai dari pengendalian proses penyidikan hingga pengambilan keputusan akhir. Jaksa akan terlibat sejak awal penyelidikan dan penyidikan untuk memastikan kelengkapan berkas dan sinkronisasi hukum. Jaksa juga berwenang memberikan arahan kepada penyidik terkait alat bukti yang diperlukan. Salah satu aspek penting dalam konsep ini adalah penerapan restorative justice, di mana kejaksaan diberi wewenang untuk menyelesaikan perkara melalui pendekatan mediasi atau rekonsiliasi. Hal ini memberikan alternatif penyelesaian perkara di luar jalur peradilan formal, yang dalam beberapa kasus bisa lebih bermanfaat bagi masyarakat. Terkait koordinasi dalam penanganan tindak pidana khusus, khususnya kasus yang melibatkan berbagai institusi seperti Polri, KPK, atau militer, Kejaksaan akan berperan sebagai pengendali untuk mencegah tumpang tindih yurisdiksi. Namun, perubahan ini juga membawa tantangan terhadap asas differensial fungsional yang selama ini dianut dalam KUHAP. Asas differensial fungsional yang memisahkan fungsi penyidik dan penuntut umum akan mengalami perubahan signifikan. Penyidik yang selama ini memiliki otonomi hingga berkas perkara dinyatakan P-21, akan berada di bawah kendali Kejaksaan.
Sebagai penutup, kejaksaan sebagai dominus litis, sudah sepatutnya diberikan kewenangan kendali penuh terhadap proses penyidikan hingga penuntutan agar dapat menjamin keabsahan alat bukti serta keadilan bagi terdakwa dan korban (in dubio pro reo). Namun, jika jaksa tetap dianggap sebagai dominus litis, tetapi tidak memiliki kewenangan dalam tahap penyidikan, maka perannya hanya sebatas pelengkap administratif dalam sistem peradilan pidana dan bukan sebagai pengendali perkara yang sesungguhnya. Perubahan sistem ini tentu akan berdampak signifikan terhadap penegakan hukum di Indonesia. Meskipun konsep ini sudah barang tentu menjanjikan efisiensi dan koordinasi yang lebih baik, perlu ada mekanisme pengawasan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, perlu pertimbangan matang dan persiapan yang memadai dari semua stake holders yang terlibat dalam menyiapkan regulasi KUHAP terbaru secara paripurna. Semoga bermanfaat.

 2 months ago
37
2 months ago
37
















































